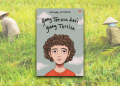“Sekarang, susah mi dapat cumi sama gurita,” keluh Daeng Nambong di suatu siang. Ia beserta dua warga lainnya tengah duduk di atas bale-bale yang berdiri tepat di depan rumah miliknya. “Kenapa begitu daeng?” tanya Suherman setelah kami berdua diajak duduk. Daeng Nambong hanya tersenyum tanpa menjawab. Hal yang sama juga terjadi pada diri Daeng Tuli dan Daeng Alle. Mereka bertiga saling bertatapan dalam diam. Suasana menjadi hening diiringi angin barat masuk ke sela-sela susunan daun kelapa yang berfungsi sebagai dinding. Kata Daeng Tuli, saat ini tengah memasuki musim angin barat sejak November lalu hingga April mendatang. Namun hujan yang harusnya turun, belum menunjukkan tanda-tanda sama sekali. Kondisi ini menunjukkan perubahan musim yang semakin sulit ditebak. Hal ini turut menjadi tantangan utama bagi para nelayan yang bermukim di Pulau Bauluang, Takalar.
Malam hari di Maret yang sama, beberapa warga sedang berkumpul di bawah rumah panggung. Lampu redup remang tampak samar menangkap wajah yang dihiasi tawa para warga yang sedang beradu canda. Saya, Suherman, Agung dan Deni lekas menuju rumah itu. Di antara mereka ada Daeng Nappa, seorang pemuda lulusan sekolah pelayaran. Sembari menikmati masa libur kerja, ia mengisi waktu hariannya dengan turun memancing ikan. “Kadang dapat, kadang tidak,” katanya menyebut kondisi hasil laut yang kurang. Suherman lalu mengulang cerita yang sempat ia dengar dari Daeng Nambong. “Kalau itumi tidak dapat, bagaimana dengan kita ini?” canda Daeng Nappa. Seluruh yang mendengar akhirnya tertawa. Kami berusaha menangkap maksud ungkapan tersebut, tak lama berselang Daeng Nappa lekas menjelaskan.
Suatu malam ia turun melaut. Barang sejam ia berhadapan dengan lautan, tidak seeekor pun yang berhasil diperolehnya. Berbeda dengan Daeng Nambong yang berada di dekat jalepa-nya. Kailnya justru berkali-kali disambar ikan. Jumlahnya mencapai tiga kilo lebih saat ditimbang pada suatu pagi di rumah seorang pengepul. “Masih kurang itu, karna biasa na dapat itu 10 kilo, kadang 13 kilo. Kadang juga 19 kilo,” kenangnya sambil tertawa. Bagi warga tempatan, Daeng Nambong dikenal sebagai “raja mancing” karena kebolehannya. Tidak hanya itu, ia dikenal pula sebagai nelayan yang punya banyak ‘channel’. Istilah ‘channel’ diartikan sebagai kemampuan berjejaring dengan orang lain di luar pulau. Persis sama dengan yang disebut Daeng Nambong siang tadi. Saat sulit mendapat hasil laut, ia memanfaatkan ‘channel-nya’ dan memilih beralih kerja sebagai buruh bangunan untuk menambah pendapatan. Dalam situasi terdesak, ia masih memiliki pilihan lain untuk mengambil pekerjaan paruh waktu di Kota Makassar.
Dua bulan kemudian, angin timur mewarnai cerita-cerita yang kami tangkap saat kunjungan Mei di Bauluang. Di berbagai sudut kampung, daun-daun kelapa tidak lagi memadati pohon. Sebagian telah dipanen untuk bahan dasar pembuatan rompong[1]. Saat hasil laut terasa mulai berkurang, menjual rompong menjadi pilihan oleh sebagian orang. Rompong bisa laku terjual dengan harga sebesar Rp.5.000/ikatnya[2]. Tiap helai yang diikatkan ini, 10 ikatnya akan digabungkan lagi menjadi satu ikatan besar dan dihargai sebesar Rp.50.000/ikatnya. Meski terlihat menjanjikan dibanding tetap turun melaut, pilihan membuat rompong di musim torani[3] bukanlah perkara mudah yang dapat ditempuh oleh semua orang. Pertama, tidak semua warga memiliki lahan. Jika ada belum tentu lahan-lahan tersebut ditanami kelapa. Kedua, pilihan memanen daun kelapa juga menjadi perkara lain yang harus dipertimbangkan matang-matang. Karena akan memengaruhi hasil panenan buah di masa mendatang.
Di tengah hasil tangkapan yang kian tidak menentu, ditambah tingginya gelombang laut karena angin kencang, melaut mungkin saja adalah pilihan berat bagi nelayan saat ini. Namun, bagi sebagian warga yang tidak punya banyak pilihan, melaut tetap harus dilakukan demi memenuhi kebutuhan hidup. Salah satunya, Daeng Se’bo. Siang hari, saya bertemu dengannya di bagian barat pulau. Area mukim beberapa nelayan selam yang menggunakan kompresor. Di belakang rumah, Daeng Se’bo beserta keluarga kecilnya tengah berkumpul di bawah rindangnya pohon kelapa. Saat itu ia bercerita seputar hasil tangkapan lautnya hari ini kepada kami. Pagi tadi pukul enam, ia sudah meninggalkan pulau menuju lokasi memancing. Namun saat kembali pukul 11 siang lewat, cumi-cumi yang diperolehnya tidak mencapai satu kilogram, bahkan tidak mampu menutupi biaya pembelian bensin. “Besok dicoba lagi to,” candanya pada kami.
Selang sehari usai bertemu Daeng Se’bo, saya lalu bertemu dengan Daeng Tola. Kami berdua tengah duduk di halaman depan rumahnya. Jauh tidak terjangkau mata, kelap-kelip lampu kapal pencari ikan memenuhi area laut malam itu. Di atas sana, bulan dan bintang gemerlapan menghiasi langit. Kami mengobrol lama ditemani gelas berisi kopi yang disajikan istrinya. “Kencangnya tadi angin,” katanya. Tak terasa hembusan angin pelan-pelan juga mendinginkan kopi yang sedang mengepul. Begitu juga saya, Daeng Tola pun demikian. Bibirnya bergetar menggigil dan bergerak tidak tentu. Seolah merekam hasil tangkapan lautnya beberapa hari terakhir yang semakin tidak menentu. Ia bercerita, petang tadi cumi-cumi tangkapannya tidak mencapai setengah kilo. Ini berarti pilihan menjual hasil tangkapan sementara waktu harus ditunda demi kebutuhan konsumsi keluarganya, meski dengan lauk cumi-cumi secukupnya. Pilihan untuk melaut di malam hari sebenarnya cukup tersedia. Tetapi Daeng Tola lebih memilih berada di rumah karena khawatir akan tingginya ombak besar dan angin kencang. Ia mengatakan, memancing peruntungan sepanjang malam tidak selalu berarti akan menambah pendapatan.
Berangkat dari cerita harian di kampung melalui proses survei mendengar yang dilakukan dua kali, kami memilih ‘hasil laut yang kurang’ sebagai tema generatif[4] yang berikutnya dikemas dalam suatu lokakarya six step deeging deeper atau enam langkah menggali lebih dalam.[5] Diskusi konsep, metode, desain dan persiapan lokakarya pun bergulir di antara para pegiat CTM. Hal ini cukup menguras banyak energi dan waktu sebab kami harus melakukan berbagai penyesuaian seperti: penyederhanaan bahasa, pernyataan maupun pertanyaan kunci yang akan diajukan. Begitu juga dengan pemilihan coding yang sama runyamnya. Saat itu kami mendiskusikan bahwa kode yang dipilih haruslah singkat dan mudah dimengerti oleh komunitas agar lokakarya dapat berjalan dengan baik. Termasuk menguji coba desain lokakarya tersebut secara berulang, sebelum lokakarya sesungguhnya dilakukan pada bulan Juni di Bauluang.

Saat lokakarya berlangsung, kami menangkap cerita dan refleksi warga tentang penyebab berkurangnya hasil tangkapan laut. Bagi mereka, biaya hidup yang semakin mahal ditambah modal yang besar untuk pembaruan alat tangkap, mendorong beberapa nelayan menggunakan cara cepat untuk menangkap ikan seperti penggunaan bom dan bius. Belum lagi keberadaan nelayan luar pengguna pukat harimau yang datang di sekitar perairan Tanakeke, turut menimbulkan kerusakan di beberapa area tangkap. Akhirnya para nelayan lokal dengan alat tangkap sederhana seperti pancing kerap menemui jalan buntu untuk bersaing dengan nelayan pengguna pukat harimau. Pilihan yang tersedia pun tidak beragam selain harus bertaruh keluar lebih jauh dari area tangkap sebelumnya yang juga kadang-kadang sama tidak menguntungkan. Namun, demi memperoleh hasil tangkapan, jalan ini tetap ditempuh meski hanya cukup untuk menutupi modal.
“Apakah ada peran pemerintah?” tanya kami melanjutkan. Dalam urusan ini, pemerintah terkesan abai bagi anggapan komunitas. Jika pun ada, belum tentu aturan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah sesuai dengan kebutuhan. Apalagi masyarakat kerap tidak dilibatkan dalam merencanakan maupun mengambil keputusan yang dapat mendukung kehidupan mereka di kampung. Bahkan dalam beberapa kesempatan, cerita seputar ‘bantuan’ dari pemerintah justru menuai konflik dalam beragam rupa. Alih-alih menjadi solusi dalam mengatasi persoalan yang tengah dialami, praktik pemberian bantuan justru memicu hadirnya ketergantungan dan retaknya hubungan sosial antar sesama warga.
“Apakah ini perlu diurus secara bersama?” kami kembali bertanya. “Perlu dan harus,” seru serempak beberapa partisipan. “Bagaimana caranya?” tanya kami kemudian. Partisipan yang terbagi dalam tiga kelompok saling berdiskusi dan merumuskan beberapa tindakan bersama. Salah satunya demi menekan dan mengurangi pengeluaran harian rumah tangga, mereka mengusulkan akan membuat media tanam dan merawat tanaman sayur di sekitar pekarangan. Merespon rencana bersama yang disusun oleh komunitas, kami melakukan kunjungan lagi pada bulan Oktober. Di antara kami yang berangkat, Syukron Pegiat ‘Kebun Tetangga’ juga turut serta sekaligus menjadi fasilitator dalam agenda belajar dan praktik ‘pertanian organik di ‘kebun pekarangan’.

Pada pertemuan tersebut, beberapa warga yang hadir tampak antusias dalam mengikuti rangkaian pembelajaran yang dilakukan oleh Syukron. Mulai dari cara membedakan tanah subur dan tidak, membuat media tanam dengan menyesuaikan sumber daya yang tersedia di kampung, melakukan pengomposan, hingga cara memanfaatkan air bilasan beras sebagai pupuk organik cair. Sebagai penutup dalam putaran belajar ini, sejumlah bibit tanaman seperti: cabai, terong, bayam, kangkung dan tomat—disemai dan memenuhi media tanam yang telah dibuat bersama-sama. Tetapi beberapa bulan setelahnya, tantangan pengelolaan ‘kebun bersama’ mulai terlihat. Benih-benih yang disemai tidak tumbuh sesuai harapan. Seluruh media tanam kering kerontang karena kekurangan air dan tidak tersiram. Sumur-sumur air tawar sebagai sumber air tampak surut. Bahkan hujan yang dinanti-nanti saat musim barat tidak kunjung tiba. Seluruh aktivitas pengelolaan ‘kebun bersama’ terpaksa harus terhenti.
Namun, benih yang tidak tumbuh dengan baik justru memicu tumbuhnya hal lain. Tantangan yang dialami oleh komunitas, justru memupuk aksi bersama dan menumbuhkan inisiatif yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Komunitas lalu memutuskan untuk memindahkan lokasi ‘kebun bersama’ dan memulai mengurusnya lagi dengan semangat yang lebih baru. Pilihan pindah lokasi tentu saja punya alasan yang kuat. Sesuai pengamatan komunitas, lokasi kedua dianggap lebih memungkinkan untuk ditanami karena ketersediaan tanah yang jauh lebih subur jika dibanding dengan lokasi sebelumnya. Apalagi lokasi tersebut merupakan bekas kandang sapi. Dugaan ini pun sesuai perkiraan warga tempatan. Sejak Desember hingga Juli kemarin, belasan rumah tangga telah berhasil memanfaatkan hasil panenan sayur yang tersedia di lahan tersebut. Mulai dari cabai, terong dan kangkung. Ada pula tomat dan bayam yang sempat dipanen sekali. Sedangkan benih lain yang baru saja di uji coba yakni pare—masih dalam masa pertumbuhan. Perlahan tapi pasti, segala usaha yang dilakukan akhirnya dapat dituai bersama.
Dari rangkaian proses yang kami tempuh dengan komunitas setahun belakangan, tentu tidak hanya memuat seputar tantangan dan keberhasilan-keberhasilan kecil yang patut dirayakan. Lebih lanjut hal ini akan terus didialogkan bersama dengan komunitas melalui proses aksi-refleksi-aksi. ‘Kebun pekarangan’ yang awalnya diputuskan sebagai tindakan dalam mengurangi pengeluaran, kini mampu mendorong tumbuhnya kerja sama antar CTM dengan warga maupun antar warga dengan warga lainnya. Hal ini tampak berjalan baik, seiring pengolahan dan perawatan ‘kebun bersama’ yang kerap kali dilakukan secara bersama-sama.
Lebih jauh, memikirkan keberlanjutan dari kebun pekarangan menjadi bagian yang tidak terpisah dari proses kunjungan yang akan kami lakukan ke depannya. Terlebih lagi, ‘kebun pekarangan’ masih dalam tahap uji coba serta akan menemukan bentuknya sebagai langkah kecil untuk pemulihan lingkungan. Misalnya dengan tetap saling belajar untuk mempraktikkan cara baik dalam pengolahan kebun secara organik, sembari pelan-pelan mengurangi ketergantungan warga akan input kimia maupun pangan seperti sayuran yang datang dari luar. Begitu pun dengan tetap mendialogkan pentingnya melihat ulang bagaimana sebaiknya cara kita berelasi dengan alam sebagai sumber kehidupan bagi generasi saat ini hingga generasi mendatang.
Sebagai akhir, saya ingin mengutip satu ungkapan dari salah seorang warga “Kebun pekarangan memberi kehidupan karena buahnya bisa di makan. Ada juga yang nakurangi pengeluarannya,” kata Daeng Tommi sembari merekahkan tawa.
[1] Bahasa Makassar, berarti alat tangkap utama yang digunakan saat mencari telur ikan terbang
[2] Seikat rompong terdiri dari 10 helai daun kelapa kering yang sudah dipisah lidinya
[3] Bahasa Makassar, berarti musim mencari telur ikan terbang
[4] Tema yang diresahkan atau paling dikeluhkan oleh warga di kampung dan berpeluang untuk menggerakkan
[5] Tahapan six step deeging deeper di antaranya: menampilkan kode, menamai masalah, merefleksikan masalah di kehidupan nyata, mendalami dampak (dirasakan dan dialami), menggali akar masalah (penyebabnya) dan menyusun rencana tindakan bersama