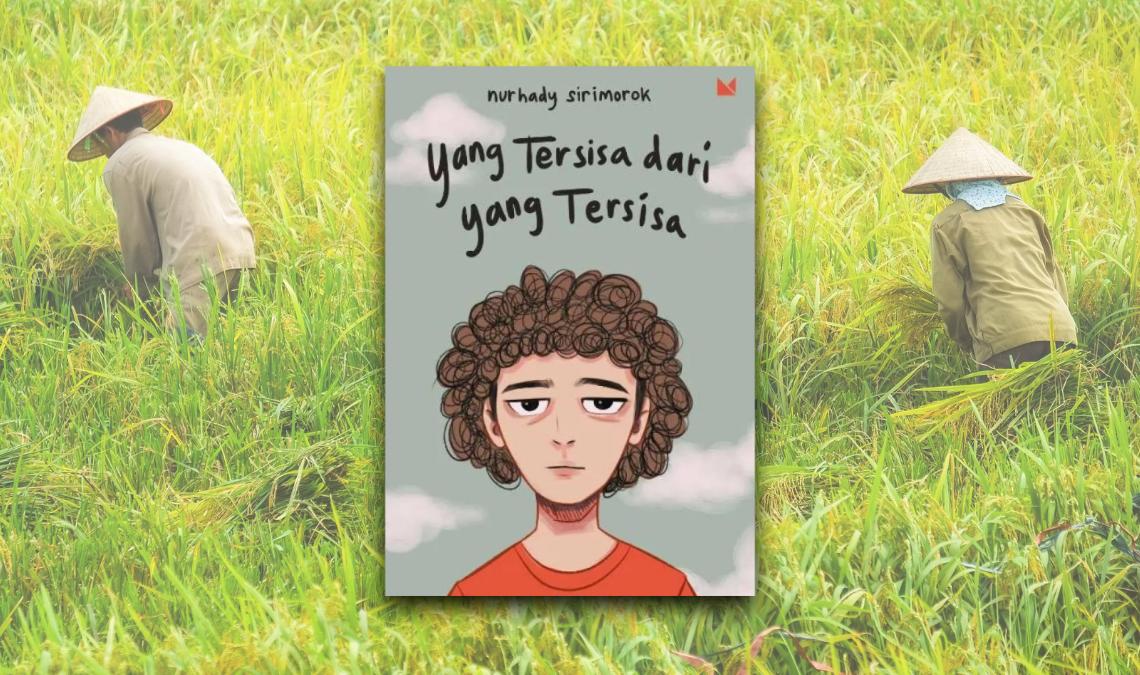Judul Buku: Yang Tersisa dari yang Tersisa
Penulis: Nurhady Sirimorok
Tebal Halaman: 183 halaman
Penerbit: Buku Mojok
Tahun Terbit: 2020
Awal-mula
Berhadap-hadapan dengan karya sastra seperti menguliti dunia yang tampak berbeda. Hasil membangun dunia rekaan dalam karya sastra tidak terlepas dari bahan baku yang meliputi interpretasi pengarang atas kenyataan (realitas) dan dalam waktu yang bersamaan turut mengerahkan kreativitas, imajinasi, serta bahasa sebagai bahan bakar.
Bahasa menjadi satu kata kunci yang harus dipeluk secara utuh sebagai seorang pengarang sekaligus oleh pembaca karya sastra. Maka memang mesti untuk memusatkan perhatian pertama-tama pada bahan bakar itu yang membuatnya tersusun dan hidup sebagai ‘sesuatu’ yang mewujud dalam dunia rekaan. Dalam hal ini, menyelami novel Yang Tersisa dari yang Tersisa karya Nurhady Sirimorok seolah membuat pembaca masuk ke dalam dunia bahasa yang tumpah secara imajiner, namun sebetulnya sangat dekat dengan situasi pelik yang betul-betul nyata dihadapi di perdesaan. Termasuk oleh setiap orang yang menggantungkan hidupnya pada tanah dan pertanian.
Pembaca akan diajak masuk ke dalam kehidupan perdesaan bernama Tompotikka dengan tengadah. Tiap-tiap hembusan nafas seolah berdampingan dengan berbagai macam masalah yang mengepung tokoh-tokoh di dalam cerita hingga semakin terjepit dalam menjalani hidup, namun hanya sebagian orang yang mengalaminya.
Semakin dalam berjalan di cerita-ceritanya, pembaca akan menjumpai bahwa dunia perdesaan terasa aneh, setidaknya jika dibandingkan dengan perspektif arus utama yang gemar meromantisasi kehidupan desa sebagai komunitas yang damai, tentram, rukun, dan seolah tidak dialiri sisi hidup yang rumit. Dunia yang asing tampak semakin mendekat. Dalam hal ini, kehadiran karya sastra tampaknya tidak ingin melepaskan diri dari peranti penyusunnya yang tidak kalah penting (baca: realitas) guna melakukan perannya dalam menyingkap fenomena-fenomena nyata yang jarang disadari, terutama di perdesaan. Novel ini berupaya menepis asumsi umum jauh sebelum mata dan telinga kita berhadap-hadapan dengan desa.
Potret Masyarakat Perdesaan dalam Novel Yang Tersisa dari yang Tersisa
Sejak halaman awal, novel ini menunjukkan perasaan putus asa yang diwakili oleh tokoh Amir sebagai remaja yang gamang melihat desanya penuh dengan muslihat dalam mengusir anak-anaknya. Di usia lima belas tahun, Amir harus meneguk kenyataan pahit bahwa ketiga sahabatnya harus pergi meninggalkan Desa Tompotikka. Mereka akhirnya meninggalkan Amir seorang diri. Ia sendiri tidak tahu persis alasan yang membuntuti kejadian itu bermula. Sebagai remaja, ia juga merasa tidak punya cukup kekuatan untuk mengerti dan mencegah kepergian ketiga sahabatnya itu.
Selain ketiga sahabatnya yang belakangan disebut sebagai Ogi, Makmur, dan Supri yang pergi meninggalkan kampung, orang-orang Tompotikka lainnya juga diceritakan telah lama berbondong-bondong meninggalkan kampung satu demi satu. Di Desa Tompotikka itulah hampir keseluruhan cerita terbangun. Namun, apa yang sebetulnya tengah dialami oleh orang-orang Tompotikka di dalam novel tersebut? Mengapa di tengah situasi pelik yang menimpa Desa Tompotikka, sebagian orang justru masih dapat bertahan tetapi sebagian lainnya terpaksa gigit jari dan harus angkat kaki?
Cerita dimulai saat tokoh Nenek mencoba mengingat kembali masa silam sebagai saksi hidup di tahun 1992, masa-masa ketika komoditas cengkeh menjadi primadona yang gandrung diproduksi di kabupaten tetangga. Kejadian tersebut berdasarkan pengamatan pembaca menjadi salah satu tonggak yang turut mengubah relasi sosial dan ekonomi antar tokoh di dalam cerita. Di masa lampau, tokoh Nenek merupakan seorang buruh pemetik cengkeh yang harus bekerja ke kabupaten tetangga pada pemilik kebun saat musim panen tiba demi melanjutkan hidup.
Seiring waktu, harapan yang hendak dituai oleh para buruh panen mendadak runtuh seketika saat harga cengkeh anjlok. Alhasil para pemilik kebun juga merasa putus asa hingga mereka membabat habis pohon-pohon cengkeh yang sebelumnya dirawat. Nenek terpaksa harus kehilangan sumber rejekinya. Ingatan ini menjadi pukulan telak bagi tokoh-tokoh rentan di dalam cerita yang sepanjang hidupnya hanya bergantung kepada orang lain demi menyambung hidup.
Fenomena semacam ini tampak seperti hamparan luas yang menuntun kita melihatnya lebih dekat. Saat tanaman cengkeh menjadi komoditas andalan yang punya nilai jual tinggi, tidak semua masyarakat di perdesaan Tompotikka dapat bersaing secara langsung dengan orang-orang di kabupaten tetangga. Tanah produktif yang tersedia di Desa Tompotikka relatif terbatas (namun pada kesempatan ini tidak diuraikan lebih jauh), begitupula kepemilikan dan akses atas tanah yang hanya dimiliki oleh sebagian orang. Jika para pemilik tanah dan modal masih dapat berspekulasi mencoba jenis tanaman lainnya, para buruh panen justru hanya dapat menelan ludah, lalu menerima keadaan.
“Keluarga-keluarga bermodal kuat yang gagal dengan percobaan menanam cengkeh, mereka jugalah yang sebelumnya membayar orang untuk meratakan tanah. Mereka melakukannya sampai semua tanah yang bisa menjadi sawah telah menjadi sawah. Sedikit sawah itulah yang menghasilkan seluruh beras di Tompotikka.” (Sirimorok, 2020: 28).
Kutipan di atas mempertegas ketimpangan kepemilikan atas sarana produksi (baik berupa tanah maupun modal) yang dikuasai hanya segelintir orang. Novel ini dengan cepat membeberkan fakta penting bahwa keluarga-keluarga yang bermodal kuat meskipun gagal dalam percobaan menanam cengkeh, mereka masih punya banyak pilihan yang lain. Termasuk membayar orang untuk menyulap seluruh tanah-tanah yang berpotensi menjadi sawah benar-benar menjadi sawah dan dapat menghasilkan seluruh beras di Desa Tompotikka.
Dengan kepemilikan aset berlebih, membuat “mereka” dapat mengontrol segala sumber daya produksi yang ada di Desa Tompotikka, hingga mencoba segala jenis pilihan yang tersedia jika mengalami kebuntuan pada satu sektor produksi. Harapan akan hidup yang lebih baik kelihatannya selalu menemui jalan yang buntu bagi beberapa tokoh yang menjalani kehidupan yang lebih runyam di kampungnya.
Ketimpangan kepemilikan atas tanah berupa sawah juga dapat diamati pada dialog tokoh remaja yang dilakukan oleh Ogi dan Amir saat membicarakan persoalan desa yang terjadi di Tompotikka.
“Nah, kalau, misalnya, seluruh orang desa batal menanam padi karena hujan tidak turun-turun juga, itu persoalan semua orang…” (Ucap Ogi)
“Bukan, itu persoalan sebagian orang. Cuma persoalan orang-orang yang punya sawah,” kataku (Amir) (Sirimorok, 2020: 19).
Menariknya, remaja seperti Amir kelihatan cukup enteng dan tajam mengamati skema penguasaan tanah di desa mereka. Baginya saat hujan tidak turun dan ketika seluruh orang desa menanam padi, itu hanyalah persoalan bagi sebagian orang, “cuma persoalan orang-orang yang punya sawah”. Ungkapan ini mempertegas ketimpangan kepemilikan atas tanah (sawah) yang menunjukkan orang-orang di perdesaan terbagi dalam kategori sosial yang tidak seragam.
Jika hanya sebagian orang saja yang memiliki sawah di Desa Tompotikka, sebagian masyarakat lainnya mungkin saja hanyalah penonton yang semakin terhimpit dan harus mencari cara lain menyiasati sumber-sumber penghidupan yang dapat diaksesnya, misalnya menjadi buruh pemetik cengkeh seperti yang telah dilakukan oleh tokoh Nenek.
Cerita berlanjut ketika musim panen telah tiba, sebagian orang di Desa Tompotikka benar-benar digambarkan sebagai penonton semata ketika karung-karung gabah mulai dijual ke pedagang.
“Begitulah, setiap musim panen, para pemilik sawah menghitung tumpukan uang yang mereka terima dari para pedagang, sementara karung-karung gabah dibanting ke atas truk. Semuanya terjadi di depan mata orang-orang Tompotikka yang ikut memanen dan menerima upah beberapa ikat gabah, yang selalu habis sebelum musim panen berikutnya tiba.” (Sirimorok, 2020: 28).
Menjadi penonton di kampung sendiri rasa-rasanya sangat umum ditemui. Namun, bagaimana jika kita menjadi penonton atas hasil keringat dan kerja yang kita lakukan sendiri? Tampak tidak adil bukan? Itulah yang diceritakan oleh tokoh Nenek dalam adegan saat Tompotikka mulai memasuki musim panen. Para pemilik sawah akan disibukkan dengan menghitung tumpukkan uang yang dihasilkan usai menjual gabah ke pedagang. Rutinitas yang hanya dapat dilakukan oleh para pemilik sawah. Sementara, bagi masyarakat yang lain, sebagai buruh yang mamanen gabah-gabah tersebut hanya mendapat upah berupa beberapa ikat gabah.
Upah yang diterima sebagai buruh panen jumlahnya seringkali tidak cukup hingga musim panen berikutnya. Kondisi ini menujukkan perbedaan yang tegas antara si pemilik sawah dan buruh panen. Keduanya memperoleh hasil kerja yang sangat berbeda. Para buruh panen yang telah bekerja justru menjadi kelompok tertentu yang menerima hasil paling sedikit, bahkan tidak mencukupi, seperti dalam kutipan “selalu habis sebelum musim panen berikutnya”. Mereka lagi-lagi digambarkan hanya sebagai penonton di samping pemilik sawah yang mencicipi keuntungan lebih besar. Seperti yang diceritakan Nenek sebelumnya, mereka hanya sibuk “menghitung tumpukan uang”.
Selain itu, lebih lanjut di dalam cerita, di Desa Bulumacene terdapat petani yang terlihat berbeda.
“Petani itu kerjanya di kota. Ia sebut dirinya petani, padahal ia sebenarnya pegawai negeri. Ia punya pendapatan bulanan, belasan sapi, dan terhitung kawanan kambing. Modalnya kuat, Kawan. Ia bisa meminjam banyak dari bank. Bank suka pada mereka, bayar cicilan pasti tepat waktu.” (Ungkap Madong) (Sirimorok, 2020: 56).
Mungkin kita telah akrab mendengar bahwa petani kebanyakan bekerja di desa-desa yang jauh dari hiruk pikuk kota. Namun, bagaimana jika ada seorang petani yang justru jarang berada di desa? Petani yang diceritakan pada kutipan di atas, ialah seorang petani yang berasal dari Desa Bulumacene, hanya saja selain bekerja sebagai petani, ia sebetulnya lebih banyak menghabiskan waktu berada di kota sebagai pegawai negeri. Meminjam istilah Habibi, petani jenis ini disebutnya sebagai “petani-kapitalis profesional”. Mereka yang memiliki pekerjaan non pertanian, berpendidikan tinggi serta pekerjaan profesional (Yistiarani, 2024). Petani yang tampak begitu berbeda dengan petani-petani pada umumnya di Tompotikka.
Meski sama-sama disebut sebagai petani, namun kepemilikan aset terlihat sangat berbeda jika dibandingkan dengan beberapa tokoh sebelumnya. Ia bukanlah petani yang menggantungkan hidup sepenuhnya hanya pada hasil-hasil pertanian mereka semata. Melainkan, juga memiliki sumber-sumber pendapatan yang lain seperti gaji bulanan dari profesinya sebagai pegawai negeri.
Selain itu, ia juga memiliki sejumlah aset kekayaan yang dikuasai secara pribadi. Hal itu membuat petani dari Bulumacene mendapat banyak kemudahan untuk mengakses pinjaman pada bank. Lembaga keuangan formal seperti bank, di dalam cerita menyebutkan suka dengan petani seperti ini karena ia dapat membayar cicilan tepat pada waktunya. Novel ini seolah ingin mengingatkan kepada pembaca bahwa kondisi tiap-tiap petani tidaklah bernasib sama dan sepenanggungan.
Perlahan-lahan saya menyelami novel ini lebih dalam. Saya membaca hidup yang tengah menggulung Desa Tompotikka. Tetapi, tokoh yang menduduki posisi strategis di desa—sekaligus memiliki dan menguasai banyak lahan—tampak biasa saja ketika masyarakat Tompotikka tengah dibayang-bayangi ketakutan atas ancaman yang akan menimpa desanya, seperti dalam kutipan.
“Ini timbangan rusak. Bisa lumpuh kita kalau terus begini,” kata Bapak. “Bayangkan, di kebun sendiri kita menyiangi kebun, menebang pohon, bakar ranting, mencangkul, menanam, merawat tanaman, dan entah apa lagi. Kita sudah capek ditambah berburu pula.”
“Sebentar lagi kita semua lumpuh.” (Sirimorok, 2020: 109).
Kegelisahan demi kegelisahan akhirnya tumpah perlahan-lahan. Bapak dari tokoh Amir merasa cemas saat mendengar serangan hama babi hutan perlahan mulai terlihat langsung di kampungnya. Masalah tersebut turut menambah bebannya sebagai penggarap kebun yang pada dasarnya sudah berat.
Semua pekerjaan yang berat itu dilakukan seorang diri sebagai petani mandiri. Sekarang beban kerja mereka harus bertambah karena mesti ikut berburu di waktu yang seharusnya mereka beristirahat. Namun, situasi genting tersebut dialami secara berbeda oleh tokoh Pak Desa. Sebagaimana dalam kutipan berikut.
“Seorang kawannya segera menimpali: Pak Desa tidak mungkin merasakan semua kesusahan mereka. Ia cuma datang melihat kebunnya dua kali, musim tanam dan panen, ia menengok penggarap lahannya sesekali saja, ia bahkan tidak pernah bermalam di kebunnya.” (Sirimorok, 2020: 109).
Pak Desa diceritakan tidak mengalami kesusahan serupa. Hal ini dipengaruhi karena Pak Desa mempekerjakan lahan miliknya kepada orang lain, sehingga ia tidak perlu repot mencurahkan tenaga kerjanya sendiri untuk mengurusi kebunnya. Dalam satu siklus produksi, ia terhitung hanya dua kali berada di lahannya, yaitu pada musim tanam dan panen. Seluruh kerja-kerja berat yang dilakukan oleh Bapak tokoh Amir, sepenuhnya diurus oleh petani penggarap yang dipekerjakan di lahannya.
Tipe petani seperti tokoh Pak Desa, dalam satu istilah disebut sebagai “petani-kapitalis-politisi-birokrat” (Yistiarani, 2024) yang menunjukkan posisi struktural sebagai pemilik tanah pertanian serta pemegang jabatan di desa. Dengan posisi seperti itu, secara bersamaan ia dapat mempengaruhi keputusan terkait hubungan produksi. Sebagai contoh, Pak Desa bisa mempekerjakan seseorang atau lebih di tanah miliknya, sehingga ia tidak perlu membuang tenaganya lebih banyak berada di kebun.
Dalam fenomena seperti ini, terdapat dua kelas sosial yang ditunjukkan dalam novel, yakni Pak Desa sebagai pemilik sarana produksi seperti tanah dan petani penggarap yang dipekerjakan di atas tanah untuk mengurusi seluruh kerja-kerja seperti yang dilakukan oleh Bapak dari tokoh Amir. Hal tersebut sekaligus menunjukkan perbandingan beban yang dirasakan oleh kedua tokoh dalam cerita—Bapak dari tokoh Amir dan tokoh Pak Desa—di tengah situasi sulit yang dialami oleh masyarakat Tompotikka.
Dengan begitu, novel ini semakin mempertegas bahwa masyarakat perdesaan terbagi dalam kategori sosial yang tidak sama. Pada mulanya dapat ditandai dengan sarana-sarana produksi (tanah dan modal) yang mulai dikelola, dikuasai, dan dimiliki secara pribadi dalam lingkup keluarga. Sementara beberapa orang di Tompotikka seperti Nenek misalnya, digambarkan harus menanggung beban lebih berat karena tidak kebagian tanah dari desanya sendiri. Ia harus luntang-lantung mencari sumber penghidupan lain dengan menjadi buruh panen di sawah maupun di kebun cengkeh yang terletak jauh di kabupaten tetangga. Penghasilan yang didapatkan pun tidak seberapa meskipun telah mencurahkan tenaganya sepanjang hari.
Kondisi itu membuat beberapa orang di Tompotikka merasa seolah dilahirkan tidak beruntung. Sementara segelintir orang, seperti Pak Desa, Petani di Bulumacene, dan “orang-orang berpunya” justru menjalani hidup mereka lebih baik karena memiliki tanah luas, modal yang kuat, serta aset kekayaan lainnya.
Itulah sedikit potret masyarakat perdesaan dalam novel Yang Tersisa dari yang Tersisa karya Nurhady Sirimorok. Lebih lanjut sebagaiamana yang dikemukakan oleh Swingewood, karya sastra adalah dokumen sosiobudaya yang dapat digunakan untuk melihat suatu fenomena dalam masyarakat pada masa tersebut. Inilah yang kemudian diistilahkan sebagai dokumentasi sastra yang merujuk pada cerminan zaman. Karya sastra ditempatkan sebagai refleksi langsung (cerminan) berbagai aspek struktur sosial, hubungan kekeluargaan, konflik kelas, trend lain yang mungkin muncul, dan komposisi populasi (Swingewood, 1972).
Penjelasan mengenai hubungan pengalaman tokoh yang kompleks melalui cerita-cerita imajiner dengan sejarah, tema, dan gaya dianggap sebagai cara yang relevan untuk mengetahui keterkaitan karya sastra dengan pola-pola kemasyarakatan yang terletak di luar teks. Hal ini menunjukkan novel Yang Tersisa dari yang Tersisa menjadi dokumen sosiobudaya yang kuat untuk mencerminkan sejumlah kenyataan masyarakat perdesaan.
“Jika melihat ke dalam satu komunitas di perdesaan, maka telah tampak perilaku yang berbeda-beda di antara orang-orang dengan hubungan agraria yang berbeda-beda pula … bahwa telah terdapat kelompok tuan tanah, penggarap tanah, pemilik modal, petani bertanah kecil, birokrat perdesaan, petani bertanah besar serta pekerja di perdesaan dan seterusnya … Secara umum seluruhnya bisa dikategorikan di dalam dan di antara kelompok “orang-orang kaya” dan “orang-orang miskin.” (Bachriadi dkk., 2021).
Membaca novel ini membuat saya merefleksikan satu karya sastra yang dilahirkan tidak terpisah dari realitas masyarakat perdesaan itu sendiri. Sebagai seseorang yang lahir dan bertumbuh di kampung, fenomena ketimpangan kepemilikan dan penguasaan atas tanah membawa saya untuk memanggil ulang ingatan masa kecil saat menyaksikan hal serupa yang juga terjadi di kampung halaman. Jika kebanyakan orang menganggap bahwa mereka yang hidup di kampung sudah pasti memiliki warisan berupa sawah atau aset kekayaan lainnya, sepertinya patut diperiksa ulang.
***
Referensi
Sirimorok, Nurhady. 2020. Yang Tersisa dari Yang Tersisa. Buku Mojok: Yogyakarta.
Swingewood, Alan dan Diana, Laurenson. 1972. The Sociology of Literature. Granada Publish Limited: London.
Yistiarani, Wida Dhelweis. 2024. Geger Gedhen di Pesisir Selatan Jawa: Pembangunan Bandara dan Dinamika Kelas Agraria di Yogyakarta. Yogyakarta: Penerbit Independen & IndoProgress.
Bachriadi, Dianto dkk. 2021. Transisi Agraria Masa Kini: Menyoal Jawaban-jawaban yang Tersedia. ARC: Bandung.