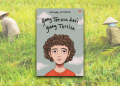Cita Tanah Mahardika dan beberapa komunitas serta organisasi mahasiswa, seperti Lesbumi, HMJ Sosiologi Agama, HMJ Ilmu Ekonomi dan Kebun Tetangga telah mengadakan nobar film “Tanah Moyangku” di Kebun Tetangga, Samata, Gowa, 14 Desember 2023. Kurang lebih 40 partisipan terlibat langsung dalam kegiatan ini.
Saya akan berbagi cerita dan pengalaman ketika ikut serta dalam nobar film dokumenter karya Watchdoc tersebut. Bagaimana para partisipan merefleksikannya, apa saja yang bisa saya petik dari cerita-ceritanya, dan kemudian bagaimana fasilitator mengunakan metode refleksi, akan tersaji dalam tulisan ini.

Sepintas tentang Tanah Moyangku
Dokumenter ini menyajikan berbagai persoalan agraria di Indonesia yang tak kunjung tuntas hingga hari ini. James Watt dan beberapa rekannya di Desa Penyang, Kalimantan Tengah sampai saat ini masih berjuang untuk mempertahankan tanahnya agar tanah mereka tidak dirampas oleh perusahaan sawit. Di Rempang, para anak muda hingga ibu-ibu, juga masih berjuang dengan sekuat tenaga untuk mempertahankan tanahnya. Peristiwa seperti ini hampir selalu terlihat dalam film.
Rupanya kejadian tersebut tak bisa dilepaskan dari akar sejarah yang panjang. Di masa lampau, kolonialisme punya andil besar menciptakan konflik agraria ini di tanah Nusantara.
Dalam sebuah adegan, peneliti KITLV Ward Berenschot dan sejarawan Indonesia JJ Rizal sedang mengobrol. Di hadapan mereka terdapat beberapa salinan dokumen: Agrarische Wet 1870 atau Undang-Undang Agraria era kolonial dan Undang-Undang Pokok Agraria atau dikenal dengan UUPA 1960 yang disusun setelah kemerdekaan Indonesia.
Dalam UU Agraria kolonial itu, diatur tentang Domein Verklaring (deklarasi wilayah), kebijakan yang menurut JJ Rizal tidak menghargai hak ulayat atau hak-hak adat. Domein Verklaring digunakan untuk memastikan tanah-tanah—yang sebagian besar tanah ulayat—yang tidak bisa dibuktikan kepemilikannya secara resmi akan diklaim menjadi milik negara, dalam hal ini pemerintah kolonial.
Narator film, Dandhy Laksono, memaparkan jika ini jelas masalah besar di era itu, sebab penguasaan tanah yang sebagian besar dikelola secara adat itu tidak mengenal kepemilikan resmi yang bisa dibuktikan dalam bentuk dokumen-dokumen administratif. Sebaliknya, wilayah kelola hanya ditandai dengan garapan, batas-batas wilayah juga ditandai dengan tanaman atau pohon-pohon tertentu, sungai-sungai, dan bebatuan.
Menurut Ward, aturan ini bisa dibilang adalah warisan yang buruk dari nenek moyangnya, sementara JJ Rizal menanggapi itu sambil tertawa. Sebelumnya, sejarawan itu mengatakan kalau Domein Verklaring masa kolonial ini memang diterapkan secara membabi buta.
Mereka lalu membahas UUPA 1960 yang dianggap cukup maju meski keduanya menganggap masih ada beberapa catatan terkait penguasaan negara atas tanah. UU ini telah mencabut Agrarische Wet beserta pasal yang mengatur Domein Verklaring di dalamnya. Namun, upaya-upaya melakukan perubahan dalam kebijakan agraria ini segera terhenti dengan terbitnya UU Penanaman Modal Asing (PMA)1967. Undang-undang ini sekaligus menandai awal kekuasaan pemerintahan Orde-Baru.

Sejak itu UUPA 1960 tak lagi menjadi rujukan utama pemerintah Indonesia dalam tata kelola pertanahan, bahkan di pemerintahan saat ini, diterbitkan UU Cipta Kerja dan UU IKN yang kian memperpanjang kasus-kasus agraria. Bahkan periode penguasaan lahan, baik untuk perusahaan swasta maupun negara, saat ini jauh lebih panjang ketimbang era kolonial.
Kemudian, dalam dokumenter ini, ada satu hal yang cukup sering ditampilkan, yaitu kriminalisasi dan banyaknya korban luka hingga korban jiwa. Berbagai tampilan itu mendukung sajian data di awal film. Dalam catatan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) yang dikutip Watchdoc, dalam kurun waktu 2015-2022, terdapat 1934 orang dikriminalisasi, 814 dianiaya, 78 tertembak, dan 69 di antaranya meninggal dunia.
Namun, dari dominasi perusahaan-perusahaan besar dalam penguasaan sejumlah besar lahan, di bagian akhir film ditampilkan juga beberapa kemenangan-kemenangan warga dalam merebut dan mempertahankan ruang hidupnya. Cerita itu datang dari ibu-ibu di Kalimantan Selatan dan para petani yang tergabung dalam Serikat Petani Pasundan. Kata kunci dalam kemenangan-kemenangan itu adalah “solidaritas”.
Beberapa Refleksi dari Partisipan Nobar
Setelah sesi nobar, Amel, pegiat Cita Tanah Mahardika yang berperan sebagai fasilitator kemudian memberikan kesempatan bagi siapa saja partisipan yang ingin menyampaikan perasaan, pandangan, dan refleksinya atas film tersebut. Sebelumnya, ia menyampaikan jika dalam refleksi ini tidak terdapat satu pembicara tunggal yang akan membedah filmnya.
Jamal, pemuda asal Desa Bakaru, Pinrang mengajukan diri lebih awal. Ia membahas bahwa soal-soal agraria yang diangkat di dokumenter ini cukup terasa di kampung halamannya. Ruang hidup orang-orang di kampungnya dihimpit oleh kehutanan dan wilayah konsesi PT PLN. Ia lalu mempertanyakan izin-izin HGU (Hak Guna Usaha) yang seringnya hanya dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar, “Apakah HGU tidak bisa diakses oleh masyarakat biasa?” tanyanya.

Hal ini ditanggapi oleh Rizal Karim, seorang pemuda yang kini aktif di Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Sulsel. Menurutnya, HGU sejauh ini memang selalu saja diperoleh perusahaan-perusahaan besar, namun HGU sebenarnya bisa juga diakses oleh koperasi yang dikelola masyarakat. Salah satu syarat untuk memperoleh izin HGU adalah berbadan hukum Indonesia. “Koperasi itu berbadan hukum, sama perusahaan juga berbadan hukum,” tambahnya.
Namun, “permasalahannya adalah akses itu hanya formalitas saja,” kata Rizal. sangat sedikit kasus dimana HGU bisa diakses oleh masyarakat atau koperasi. Sebab, pemberian izin HGU itu juga sangat dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan ekonomi-politik yang berkuasa di belakangnya. Di samping itu, perlu modal yang cukup besar dan melalui langkah-langkah administrasi yang rumit. Itu membuat posisi masyarakat dalam mengakses itu tidak sama dengan perusahaan.
Hal ini juga berkaitan dengan penelitian Ward yang dipaparkan dalam dokumenter. Dalam meneliti ratusan kasus agraria di Indonesia yang ia bukukan dengan judul Kehampaan Hak, menurutnya, hak-hak masyarakat itu bukannya tidak ada, sebenarnya ada, tapi tidak pernah diberikan, sehingga itu hanya menjadi kehampaan.
Sementara itu, Bambang, pemuda asal Ternate, mengungkap jika kampungnya adalah salah satu wilayah tambang nikel terbesar di Indonesia. Menurutnya, akhir-akhir ini, ia khawatir dan bingung. Arah pembangunan kian kabur dan makin banyaknya kasus perampasan ruang hidup yang difilmkan Watchdoc.
“Perampasan ruang ini hanya bisa kita batasi dengan solidaritas,” kata Bambang.
Hal yang serupa disampaikan oleh Mail, mahasiswa Ilmu Ekonomi UIN Alauddin Makassar, bahwa kasus-kasus perampasan ruang akan terus-menerus mengancam siapa pun. “Saya, kita, dan kawan-kawan di sini akan terus dibayang-bayangi penggusuran,” katanya. Baginya, dengan bersolidaritas kita bisa menghadapinya.
Imamul Hak, buruh akademik salah satu kampus negeri di Gowa, menyinggung kembali bahwa HGU yang banyak disentil di film dan diskusi ini memang selalu dimenangkan dan dikuasai oleh korporasi besar dengan sistem ekonomi-politik yang ada sekarang. Namun ada cerita menarik dari koperasi yang dikelola penyadap karet Tasikmalaya, Jawa Barat, yaitu Koperasi Wangunwatie.
Mereka mungkin, bisa jadi adalah salah satu—jika bukan satu-satunya—koperasi di Indonesia yang berhasil mengakses hak atas HGU. Itu melalui proses yang panjang, persiapannya dari era kolonial. Caranya adalah menguasai kembali lahan-lahan yang dulu dikuasai oleh kolonial dengan cara menggarapnya bersama. Sebab, “Menguasai itu adalah menggarap,” tambahnya.
Film ini lalu mengantarnya pada satu kegelisahan lain, yaitu ketimpangan. Di film itu digambarkan bahwa perusahaan besar yang dikuasai oleh segelintir orang menguasai sebagian besar ruang atau wilayah. Sementara, kita orang-orang biasa, sebagian besar termasuk dalam orang-orang yang dirugikan dalam ketimpangan itu.
Agung, dalam refleksinya, ia memulai dengan membedakan antara istilah kepemilikan dengan penguasaan. Kepemilikan biasanya digunakan bagi mereka yang memiliki sertifikat, tetapi kalau penguasaan itu tidak.
“Seseorang yang tidak memiliki status kepemilikan itu bisa menguasai, dalam artian ia bisa mengelola, memanfaatkan atau mempergunakan tanah tersebut,” ungkap Agung setelah membahas banyaknya istilah dibuat di era pemerintahan Soeharto yang mengaburkan masalah agraria.
Sementara menurut Amel, di sepanjang film, ada banyak perempuan yang terlihat turut berjuang. “Mereka para ibu dan anak-anaknya menjadi kelompok yang paling rentan,” tambahnya. Mereka akan memikul banyak beban-beban berat jika terjadi kriminalisasi, kekerasan, dan perampasan atas lahan mereka.
Dalam kesempatan ini juga, pengelola Kebun Tetangga, Syukron, berbagi pengalamannya dalam mengelola kebun. Lahan yang mereka kelola ini dimiliki oleh kampus Nobel, dipercayakan untuk dipakai bertani, beternak, dan berkebun. Tidak ada surat menyurat, ia hanya memanfaatkan ruang.
Ia mengimbau bagi yang ingin belajar berkebun untuk datang saja ke Kebun Tetangga. Mereka akan menerimanya dengan senang hati, mereka juga telah menyediakan rumah bagi siapa saja yang mau menginap sembari menunjukkan tempatnya.
Mengapa Refleksi?
Sebagai salah satu peserta nobar, menarik melihat model refleksi ini. Ini terinspirasi dari metode dialogisnya Freire. Saya pernah mempelajarinya ketika mengikuti sesi pengenalan Paulo Freire di Training for Transformation (TFT) beberapa waktu lalu.
Fasilitator saat itu, Dian Yanuardy, menunjukkan gambar seseorang mengisi kepala orang lain dengan gagang selang bahan bakar minyak. Yang satunya berdiri dengan setelan rapi, yang satunya duduk pasrah diisi terus menerus. Kami diminta menamai gambar itu. Beberapa menganggap inilah gambaran pendidikan gaya bank. Beberapa yang bilang “ada yang berkuasa dan ada yang dikuasai,” dan lainnya menganggapnya sebagai pendidikan satu arah.
Model itulah yang berlaku di pendidikan kita sejauh ini. Pendidikan yang melahirkan budaya ‘diam’, bukannya dialog.
Sebaliknya, dalam nobar dan refleksi ini, kita bisa mulai pelan-pelan memberikan ruang untuk orang-orang banyak berbicara dan merefleksikan perasaan, pandangan, serta pengalamannya terhadap suatu isu atau masalah, meski tentu saja masih perlu terus membiasakannya.
***