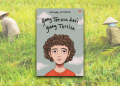Berbekal pengalaman selama di kampung, tulisan ini mencoba menceritakan kisah nelayan patorani di Bauluang. Sebagai orang dari luar komunitas, selalu ada jarak antara saya dengan mereka (para patorani). Namun, sebagaimana seharusnya tugas pengamat, selain terlibat langsung dengan subjek yang ditelitinya, mereka juga dituntut untuk memangkas jarak untuk memperkecil adanya bias. Sehingga, dalam kasus tulisan ini, yang saya lakukan hanyalah menjembatani pengalaman personal saya (termasuk perasaan dan cara berfikir) dengan apa yang sedang terjadi di kampung untuk menjelaskan tindakan, cara pandang, serta hubungan-hubungan yang terjalin di antara mereka.
Sejarah Nelayan Patorani
Saya tidak mengira akan basah kuyup ketika sampai di Bauluang. Ombak yang semula tenang, mengamuk di tengah perjalanan. Memang benar, musim timur cuacanya lebih sulit ditebak—seperti kebanyakan yang dituturkan oleh para nelayan. Pada musim timur juga lah, Bauluang akan tampil dengan ritme yang berbeda dari biasanya. “Sekarang, lagi musim torani,” kata warga setempat.
Kapal-kapal kecil yang seharusnya dilayarkan menuju lautan terparkir di sepanjang bibir pantai karena cuaca sedang tak baik. Para lelaki yang biasanya kami temui tidak pergi melaut. Mereka tampak sibuk memperbaiki kapal yang bukan miliknya—dengan ukuran yang jauh lebih besar dari yang ia punya. Sementara warga yang lainnya memungut pundi-pundi pendapatan dari pohon kelapa yang tinggi menjulang. Mereka memanjat, membabat, dan mengupas lidi dari daun kelapa untuk bahan baku rumpon yang tiap tangkainya akan dihargai 3 – 5 ribu rupiah.

Melihat situasi langsung di kampung, saya lalu penasaran mengapa orang yang mencari telur ikan terbang disebut patorani—sebagaimana rasa penasaran saya terhadap penamaan lokal untuk jenis-jenis ikan berbeda yang jumlahnya sangat banyak itu. Untuk topik ini saya tidak mendapat penjelasan langsung dari orang-orang yang saya temui di Bauluang. Di lapangan, rasa keingintahuan kerap harus dibawa pulang sebagai pekerjaan rumah.
Informasi itu justru saya dapatkan dalam Nelayan Makassar Kepercayan, Karakter (2012) yang ditulis Prof. Dr. Tadjuddin Maknun, S.U. Menurut Guru Besar Ilmu Linguistik Fakultas Ilmu Budaya Unhas itu, pada 1 Agustus 1667, Galesong yang merupakan basis pertahanan kerajaan Gowa saat itu berupaya diduduki oleh Belanda dan sekutunya karena letaknya yang strategis. Kala itu pertempuran berlangsung sengit, namun pendudukan Belanda pada akhirnya tidak mendapat perlawanan yang berarti. Melihat kondisi tersebut, Karaeng Bonto Marannu bersama pasukannya meloloskan diri dengan membawa persenjataan dan sebilah keris emas menuju benteng induk pertahanan Gowa dan berniat untuk menyerang kembali pasukan Belanda di Galesong.
Pada 18 Agustus 1667, di bawah pimpinan Polan, pasukan Belanda bergerak menuju Galesong untuk bergabung dalam peperangan bersama pasukan Belanda lainnya yang sudah ada di sana. Esoknya, benteng di Galesong digempur oleh Belanda melalui serangan yang datang dari dua sisi, darat dan laut. Pada akhirnya Benteng Galesong jatuh. Akibatnya, pihak Gowa mengajukan gencatan senjata dengan pihak Belanda yang saat itu diwakili oleh Speelman.
Dalam proses kompromi tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk melahirkan satu kesepakatan yang dikenal dengan “Perjanjian Bungaya.” Kesepakatan tersebut tidak sepenuhnya disepakati oleh pihak Gowa. Pihak Karaeng Galesong, yakni I Manodari Karaeng Tojeng bersama Karaeng Bonto Marannu yang tidak sepakat dengan perjanjian tersebut, memilih untuk tetap berperang melawan Belanda. Selanjutnya, keduanya diketahui meninggalkan Butta Gowa dan Galesong menuju Lake, Pulau Satangnga, Pulau Baulung (Bauluang) dan Pulau Dayang-dayangan untuk mempersiapkan 70 armada dan puluhan ribu pasukan untuk berlayar menuju Banten, Jawa Barat.
Dalam perjalanan tersebut, pasukan Karaeng Galesong menangkap ikan di sepanjang selat Makassar. Kebanyakan ikan yang tertangkap adalah jenis ikan terbang. Ikan-ikan tersebut lalu dibawa pulang ke Galesong untuk diawetkan. Masyarakat Galesong penasaran dengan banyaknya ikan yang tertangkap dan bertanya “Siapa yang membawa ikan banyak sekali?” Pekerja Karaeng Galesong pun menjawab “To baranina karaenga” (Seorang pemberani utusan raja). Sejak saat itu, ikan terbang mulai populer disebut jukuk torani. Sementara mereka (nelayan) yang menangkap jukuk torani kemudian disebut sebagai patorani.
Keterikatan orang Bauluang pada torani sudah terjalin secara turun-temurun. Sejak lama, orang Bauluang sudah dikenal sebagai patorani. Daeng Emba, lelaki yang berusia senja (70 tahun), dengan bayang ingatan yang hampir tenggelam dimakan usia, menjelaskan secara perlahan pada saya sejarah nelayan patorani di Bauluang. Menurutnya, sejak dimulainya patoraniang yang berlangsung pada 1940an, ada banyak perubahan hingga sekarang ini. Cara mereka menangkap, teknologi yang digunakan, serta target yang mereka buru untuk ditukarkan ke pasar berubah sepanjang sejarah.
Sekitar tahun 1960an, para patorani hanya menargetkan induk ikan terbang atau tuing-tuing. Mereka mengumpulkan induk tuing-tuing dengan menggunakan pakkaja, perangkap yang terbuat dari bambu yang lebih umum dikenal dengan nama bubu hanyut. Dalam sekali melaut, sekitar 20-30 pakkaja dimuat dalam perahu dan akan digunakan ketika sampai di wilayah perburuan.
Pada masa itu pula, teknologi pelayaran masih terbatas, dan perahu layar masih menjadi barang langka. Tidak semua orang punya perahu layar. Perbedaan jenis layar pun menunjukkan strata sosial masyarakat. Orang yang tergolong miskin, menurut Daeng Emba, hanya menggunakan layar dari anyaman daun rumbia yang disebut karorok. Sedangkan mereka yang tergolong kaya lebih banyak menggunakan kain putih (kaci) sebagai layar. Kedua bahan tersebut, didapat di Pattalassang (Takalar) dengan cara dibeli, dan harga yang tentu saja berbeda. Layar berbahan kain lebih mahal dari anyaman rumbia.
Meskipun demikian, layar tetap layar. Apapun bahannya, ia hanya mampu mendorong perahu untuk bergerak dengan bantuan tiupan angin. Sehingga, pelayaran pada masa itu menjadi terbatas. Mobilitas nelayan pun terbatas dalam menjual hasil tangkapan secara cepat. Keterbatasan gerak dan belum adanya es untuk mencegah pembusukan ikan—barangkali merupakan alasan yang paling utama—mengapa orang Bauluang pada masa itu hanya menjual ikan kering.
Ikan kering yang disebut jukuk cekla oleh mereka akan dijual ke darat setiap dua minggu sekali setelah dikumpulkan terlebih dahulu. Hasil penjualan tersebut biasanya akan digunakan untuk membeli bahan pangan seperti terigu, ubi, jagung hingga beras. Selain untuk dijual, ikan terbang juga banyak dikonsumsi sebagai lauk dalam keluarga inti pada masa itu.
Maju satu dekade—dimulai pada 1970an sampai sekarang, pamor induk ikan tuing-tuing menurun seiring dengan naiknya harga telurnya.¹ Sebelumnya, telur ikan terbang tidak terlalu diminati dan hanya menjadi tangkapan sampingan. Ada tidaknya telur ikan yang ditangkap juga bukan masalah.
Di masa itu telur ikan terbang hanya akan dijadikan campuran sayur untuk dikonsumsi—jika tidak dijual dengan harga yang lebih murah, dideret menggumpal bagai lawi-lawi (anggur laut) seperti yang banyak ditemui di pasar-pasar yang ada di Galesong. Berbeda dengan sekarang, sedikit banyaknya jumlah telur ikan yang diperoleh patut diperhitungkan. Sebab bagi para pencari telur, ongkos produksi menjadi taruhannya.
Setelah induk ikan tuing-tuing tidak menarik lagi di mata para patorani, teknologi penangkapannya pun ikut berubah. Pakkaja atau bubu perlahan ditinggalkan jika ingin mencari telurnya. Ikan terbang, berdasarkan cara pemijahannya, termasuk dalam golongan jenis ikan fitofil, yakni ikan yang mengeluarkan telurnya pada tumbuhan atau benda terapung. Nelayan butuh media baru, khusus untuk menjaring telur.
Sejak itu juga penggunaan alat tangkap rumpon yang terbuat dari daun kelapa mulai diterapkan. Rumpon yang digunakan dalam menjaring telur ikan terbang yang oleh para patorani di Bauluang disebut balla-balla. Penggunaan rumpon kemudian berkembang seiring waktu dan masih menjadi alat tangkap yang masih populer hingga hari ini.
Belakangan, perahu yang digunakan untuk berburu pun mulai menggunakan mesin sebagai penggerak kapal untuk menjelajahi lautan dan mencari wilayah-wilayah yang produktif yang diperkirakan berlangsung sejak tahun 1980an. Selain itu, alat eletronik lain sebagai alat bantu penangkapan mulai digunakan, seperti GPS, Fish Finder, dan Handy Talkie (HT). Dengan begitu, pengetahuan navigasi terdahulu tidak lagi menjadi satu-satunya perangkat yang digunakan oleh nelayan dalam membaca dan menentukan arah wilayah-wilayah perburuan.
Tantangan, Ritual dan Pantangan
Pada 2023 lalu, dalam ingatan Daeng Ewa, terdapat 3 kapal mengalami kecelakaan. Satunya merupakan kapal nelayan parrengge, sementara dua kapal lainnya adalah kapal nelayan patorani. Kapal parengge tersebut tertabrak oleh kapal tanker ketika sedang ditarik oleh kapal lain karena macet. Sedangkan kapal patorani itu tenggelam karena dihantam ombak. Kapal torani pertama mengalami kecelakaan saat dihantam ombak dengan posisi miring, sementara kapal yang kedua terbelah saat melawan ombak. Kabarnya kapal yang kedua memang sudah berumur lebih tua.
Patoraniang adalah pekerjaan yang penuh tantangan. Tidak ada yang tahu pasti apa yang akan terjadi di tengah lautan. Keselamatan? Hasil tangkapan? Tidak ada yang dapat memastikan keduanya. Selama masa perburuan yang berlangsung hingga hampir dua bulanan—yang ada hanya kemungkinan-kemungkinan. Barangkali, satu-satunya yang pasti adalah amukan ombak yang saling berkejaran tanpa henti. Beberapa nelayan yang sebelumnya terlibat mencari telur ikan terbang, punya alasan berbeda-beda untuk tidak mencari, antara lain, kondisi fisik, umur, dan mabuk laut. Sedang beberapa lainnya, yang masih menekuni pekerjaan ini berharap dapat kembali dengan selamat.
Untuk kembali dengan selamat, juga dengan hasil yang memuaskan, ritual dan pantangan akan bekerja seperti rambu-rambu lalu lintas. Rambu-rambu ini mengatur apa yang harus dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam proses pencarian telur ikan terbang. Sebelum patorani pergi mencari, beragam jenis ritual mesti dilakukan.
Saat kondisi kapal telah siap, para patorani akan mengadakan accaru-caru terlebih dahulu sebelum dilayarkan. Ritual ini dilakukan untuk mendoakan perahu agar diberi keselamatan oleh yang maha kuasa selama pelayaran berlangsung. Accaru-caru biasanya dilakukan dengan mengadakan pakrappo atau sajian yang terdiri dari unti teknek, songkolok putih hitam, kue lapis warna hijau putih, daun sirih, umba-umba (onde-onde), daun sirih, ayam jantan dan betina, serta tebu.

Masing-masing item dalam sajian-sajian itu mengisyaratkan doa-doa baik untuk para patorani. Misalnya, umba-umba menjadi pengharapan bagi para patorani agar rejeki bermunculan—sebagaimana proses pembuatan umba-umba ketika mendidih pasti muncul ke permukaan (mengapung). Selain itu, ada juga kue lapis bermakna agar rejeki yang didapat oleh para patorani juga akan berlapis-lapis; unti teknek sendiri berisi harapan bahwa mereka akan memperoleh kesejahteraan lahir dan batin sebagaimana rasa manis dari pisang raja ini; dan item-item lainnya bermakna sebagai simbol penghormatan kepada para leluhur dan mahluk lainnya.
Pada tahap selanjutnya, ketika kapal akan dilayarkan, para patorani akan menurunkan sajian (pakrappo) tepat di antara pertemuan air dangkal dan dalam yang disebut biring bayangang. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada masing-masing penguasa di perairan dangkal dan dalam. Sementara itu, berjarak hingga ratusan mil bahkan ribuan mil dari keberadaan para patorani, doa-doa senantiasa dilafalkan dari kejauhan. Para keluarga yang ada di rumah akan membakar kayu di sekitar rumah, biasanya ditaburi garam atau gula, untuk meminta keselamatan dan rejeki selama melaut yang oleh mereka sebut “maparorok”.
Sedangkan untuk informasi mengenai pantangan-pantangan, mengalir dalam tuturan Daeng Bani saat kami tengah duduk bersama di rumah Daeng Toro.² Menurut Daeng Bani, ketika melaut ucapan benar-benar harus dijaga. Misalnya, untuk menyebut garam diganti ba’ra, “Daeng Bau” untuk ikan terbang, ba’nyara untuk vetsin, dan tallasi ketika hendak membuang sesuatu ke laut.
Selain itu, selama berada di laut, para pencari tidak boleh membersihkan kapal. Sekotor apapun itu, kondisi kapal dibiarkan begitu saja. Kapal hanya boleh dibersihkan ketika sedang singgah di pulau-pulau terdekat. Biasanya, para pencari akan beristirahat di pulau sekitar. Hal lain yang tidak boleh dilakukan adalah mengeluh.
Entah mengapa seseorang yang mencari telur ikan terbang harus menyebut beberapa benda dan aktivitas dengan sebutan lain? Mengapa ada larangan untuk mengeluh? Padahal panas matahari tak henti-hentinya menyengat kulit para patorani.
Daeng Bani memberi gambaran saat itu. Suatu waktu ia pernah mengeluh dan tanpa sengaja berujar “Sarring’i bambang” (teriknya matahari) ketika tengah melaut. Tak lama setelah itu, badai datang secara tiba-tiba dan mengejutkan Daeng Bani, juga kru lainnya. Karena kelakuannya itu, ia akhirnya mendapat teguran dari si pinggawa kapal (nahkoda) dan diberi peringatan untuk menjaga tuturannya selama di laut.
***
Catatan Kaki ¹Penanda tahun diperoleh saat melakukan FGD dengan nelayan ²Kami melakukan diskusi bersama di rumah Dg. Toro dengan para warga lainnya pada 18 Mei 2024
Daftar Bacaan Maknum, Tadjuddin. 2012. “Nelayan Makassar Kepercayaan, Karakter.” Identitas Universitas Hasanuddin, Makassar.