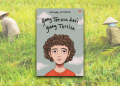Masyarakat Tanakeke secara umum meyakini kalau Pulau Satangnga pertama kali didiami oleh para nelayan dari Galesong.¹ Pada mulanya Pulau Satangnga adalah tempat persinggahan. Dahulu nelayan-nelayan Galesong seringkali singgah ke pulau ini, terutama ketika cuaca sedang buruk yang tidak memungkinkan mereka untuk segera kembali ke Galesong.
Sumber daya alam yang tersedia di Pulau Satangnga juga membuatnya sering disinggahi, terutama karena memiliki air tawar. Sumber pangan yang tersedia juga memungkinkannya jadi tempat bertahan untuk waktu yang cukup lama. Pohon kelapa, pohon sukun dan beberapa tumbuhan lain yang belum terindetifikasi kala itu tumbuh subur di dalamnya.
Konon, berdasarkan tuturan Daeng Ngagi Kamase (80 tahun), Pulau Satangnga dulunya dikelilingi oleh tumbuhan bakau yang tumbuh subur. Selain itu, terdapat pula batu karang Ta’pappang di sebelah barat pulau dengan tinggi kurang lebih lima belas meter yang bisa berfungsi sebagai pemecah ombak dan penghalang angin kencang. Itu membuat pulau ini bukan hanya sekadar memiliki sumber daya, tapi juga aman untuk ditinggali.
Ekosistem laut yang masih terjaga membuat ikan begitu berlimpah di sekitar pulau sehingga sangat mendukung aktivitas memancing nelayan. Ini menjadi salah satu alasan kuat bagi beberapa nelayan Galesong mulai melihat peluang menetap di Pulau Satangnga. Ini dikonfirmasi oleh para orang tua di sana. Mereka mengatakan kalau di masa lalu untuk mendapatkan ikan itu tidak begitu sulit. Juga tidak perlu keluar terlalu jauh untuk mencarinya, bahkan dengan teknologi yang sangat sederhana. Menyelam dan memancing di sekitar pesisir sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan harian rumah tangga nelayan di masa itu.
Nelayan-nelayan Galesong yang berencana menetap di Pulau Satangnga, perlahan mulai membangun rumah sederhana dan mengajak serta anak istri mereka untuk tinggal di sana. Tinggal di pulau berarti dapat menghemat banyak waktu dan tenaga. Sebelumnya, mereka membutuhkan waktu dan tenaga yang lumayan besar jika harus selalu pulang pergi dari Galesong ke lokasi memancing yang cukup jauh.
Di usianya yang telah cukup lanjut dengan ingatan yang mulai memudar, Daeng Ngagi Kamase mencoba merangkai satu persatu kisah masa lalunya ketika pertama kali menetap di Pulau Satangnga. Ia mengenang, ia diajak oleh ayah dan ibunya untuk tinggal di pulau ini ketika masih sangat belia. Menurutnya, pemukim awal—yang semuanya adalah keluarga nelayan asal Galesong—tinggal di area tengah pulau yang disebutnya sebagai kampong tangngayya atau kampung tengah. Sekarang, area ini disebut juga sebagai kampung tua. Seingatnya, saat itu telah terbangun sekitar 20 rumah kayu sederhana oleh pemukim, termasuk ia dan keluarganya.
Mungkin, seperti itulah sepenggal cerita bagaimana nelayan-nelayan Galesong mulai menetap di Pulau Satangnga, beregenerasi dan hidup di dalamnya hingga saat ini. Namun jauh sebelum itu, pulau ini memang sudah seringkali menjadi persinggahan.²
Di masa lalu, Pulau Satangnga yang merupakan bagian dari Kepulauan Tanakeke telah menjadi area strategis. Ditemukannya sebuah meriam berlogo VOC dengan tahun produksi 1770 di Satangnga dan 1776 di Bauluang menguatkan asumsi keberadaan meriam tersebut di periode VOC. Pulau Satangnga dijadikan sebagai salah satu pos militer kolonial. Keberadaan pos militer itu diduga untuk mengamankan kebutuhan atas cadangan air selain sebagai tempat persinggahan.

Sementara itu, di sebelah utara Pulau Satangnga juga terdapat Pulau Dayang-Dayangang. Di pulau kecil itu terdapat sebuah mercusuar yang bangunannya menggunakan bata merah. Melihat struktur bangunannya, itu diduga kuat dibangun di masa Hindia-Belanda.
Pulau ini juga punya kaitan dengan sejarah peperangan di perairan Tanakeke. Perseteruan Laksmana Cornelis Janszoon Speelman dengan Sultan Hasanuddin terkait terbunuhnya orang Belanda di Pulau Don Duongo (sekarang Pulau Dayang-Dayangang) menjadi salah satu pemicu meletusnya perang Makassar.² Di periode itu (abad 17), Kepulauan Tanakeke dijadikan sebagai tempat persinggahan dalam ekspedisi-ekspedisi Speelman ke Makassar.⁴
Selain itu, Kepulauan Tanakeke juga strategis secara geografis karena berada cukup dekat dari pelabuhan Makassar yang merupakan salah satu pelabuhan terpadat dan tersibuk di dunia pada abad ke 18.
Bentang Geografis Pulau Satangnga
Pulau Satangnga secara administratif dikelola oleh Pemerintah Desa Mattiro Baji, Kecamatan Kepulauan Tanakeke, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Sebelum pemekaran pada tahun 2022, Desa Mattiro Baji mencakup tiga gugusan pulau kecil yakni Pulau Bauluang, Labbo’ Tallua, dan Pulau Satangnga. Pulau Bauluang dan Pulau Labbo’ Tallua kini telah masuk dalam administrasi Desa Minasa Baji.

Sebagai pusat pemerintahan Desa Mattiro Baji, Pulau Satangnga rencananya akan dibagi lagi ke dalam tiga atau empat dusun, namun belum terlaksana sejauh ini. Kelengkapan administrasi pemerintahan Desa Mattiro Baji belum terlalu rapi setelah pemekaran dilakukan, seperti belum dibentuknya dua dusun yang lain.⁵
Sejauh ini ada dua dusun di Pulau Satangnga, yaitu Dusun Satangnga Lau’ dan Dusun Satangnga Raya. Satangnga Lau’ berada di sekitar makam ikan paus yang pernah terdampar dan ditemukan oleh salah satu warga (Daeng Kanang) pada 2015 silam. Sedangkan Satangnga Raya areanya berada di sekitar meriam peninggalan VOC.
Akses penyeberangan dari daratan Takalar untuk ke Pulau Satangnga membutuhkan waktu satu hingga dua jam perjalanan dengan mengendarai perahu jolloro. Belum ada kendaraan tetap yang rutin pulang dan pergi dari daratan Takalar ke pulau setiap waktu.
Penyeberangan memungkinkan terjadi setiap pagi hari ketika cuaca sedang baik. Pedagang-pedagang dari Satangnga sering menyeberang untuk membawa ikan yang hendak dijual di darat. Para pencari kayu hanyut di laut untuk bahan baku pembakaran batu merah di Takalar juga kerap menyeberang. Begitupun pedagang barang eceran untuk kebutuhan rumah tangga di pulau. Para pedagang inilah yang biasanya ditumpangi warga Satangnga ketika hendak menyeberang ke Boddia, Galesong. Tamu dari luar yang hendak ke pulau juga biasanya menumpangi perahu para pedagang.
Perubahan Sosial dan Lingkungan di Satangnga
Di Pulau Satangnga telah dibangun sebuah pelabuhan pada tahun 2019 dan dinamai sebagai Pelabuhan Tanakeke. Pelabuhan itu dibangun di Satangnga karena perairannya dianggap lebih dalam dibandingkan dengan pulau lain di sekitarnya. Alasan ini juga hadir karena kapal dapat keluar masuk membawa alat berat dan bahan material untuk pembangunan pelabuhan. Selain itu, ketersediaan air tawar di Satangnga dianggap cukup memenuhi kebutuhan pembangunan dan kebutuhan para pekerja pelabuhan. Pada tahun 2022, pelabuhan ini telah rampung dibangun, namun belum berfungsi sampai saat ini.
Di sisi barat Pulau Satangnga terdapat tumpukan bunga karang yang dibawa oleh arus laut. Salah seorang warga Satangnga menyebut bunga karang tersebut mencapai lima belas meter ketinggiannya dan luasannya diperkirakan kurang lebih sekitar seratus meter persegi. Pembangunan rumah batu di Satangnga dan beberapa titik proyek pembangunan desa seperti jalan setapak mengambil bahan material dari bunga karang itu untuk campuran semen. Bunga batu karang itupun perlahan terkikis dan menipis karena hal demikian.

Rumah Batu: Ukuran Kemajuan
Di pulau yang kelilingnya kurang lebih satu kilometer ini terlihat banyak rumah berdinding beton. Menurut perkiraan seorang warga Satangnga yang berprofesi sebagai pekerja rumah batu di pulau, saat ini rumah kayu itu jumlahnya kurang dari sepuluh unit. Meski terdapat beberapa rumah kayu, kolongnya sudah digabungkan dengan dinding beton. Jenis rumah kayu seperti ini kadang digunakan untuk beragam aktivitas rumah tangga, seperti memasak, kumpul keluarga, dan lainnya. Aktivitas keluarga lebih sering dilakukan di kolong-kolong rumah ini.
Bagi Daeng Sakking dan beberapa orang Satangnga, membangun rumah batu adalah impian dan harapan. Rumah batu dianggap lebih nyaman dan kelihatan lebih bagus. Menurutnya, rumah yang ditinggalinya sekarang belum selesai. Sebab, sebagian dinding rumah masih menggunakan kayu. Ia akan tetap berusaha untuk memperbaikinya jika memiliki modal di kemudian hari.
Seorang warga Dusun Satangnga Raya lainnya, Daeng Sugi, menceritakan kisah rumah yang ditinggalinya sekarang. Dulu rumah tersebut masih berupa rumah kayu. Ia mengenang, masa ketika meninggali rumah kayu bersama suami dan anak-anaknya adalah masa-masa sulit bagi keluarganya. Di masa itu, selain ia tinggal di rumah kayu, suaminya, Daeng Tarang, jatuh sakit. Ia kemudian menjadi tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah sepenuhnya. Daeng Sugi bahkan ikut menyelam untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Ia merasa bersyukur karena rumahnya akhirnya dapat diperbaiki dan menjadikannya rumah batu. Ia menganggap jika perekonomian keluarganya jadi lebih maju dibandingkan ketika masih berumah kayu. Baginya, itu nyaman dan membanggakan.
Warga Satangnga juga menganggap bahwa keberhasilan dan kemajuan keluarga bisa dilihat dari rumah yang dibangunnya. Hal ini dituturkan oleh Daeng Ngagi’ Kamase (70 tahun) yang tinggal di Dusun Satangnga Raya. Ia dulunya tinggal di kampung tangngayya. Ketika dia dan keluarganya masih tinggal di sana, seingatnya masih terdapat dua puluhan rumah kayu. Namun karena dianggap berat olehnya ketika membantu dan mengantar jemput suaminya yang ingin pergi melaut atau saat datang tengah malam atau subuh dini hari, ia mulai berpikir untuk pindah ke sekitar bibir pantai.
Ketika suaminya tutup usia ia masih menempati rumah kayu yang lama. Sekarang ia bersama anak perempuannya telah tinggal di sebuah rumah batu yang dibangun sekitar tiga tahun lalu. Daeng Ngagi’ Kamase merasa ketika ia dan keluarganya menempati rumah kayu, ia merasa bahwa dirinya tertinggal di antara warga lainnya yang sudah membangun rumah batu lebih dulu.

Untuk membangun sebuah rumah batu di Satangnga, batanya mesti dibuat sendiri oleh warga yang ingin membangun rumah. Untuk keperluan ini, dibutuhkan semen sekitar dua puluh sak dan pasir sekitar dua truk. Sedangkan untuk kebutuhan pondasi rumah membutuhkan batu karang sebanyak empat truk dan pasir untuk timbunan dibutuhkan kurang lebih lima truk. Selain itu diperlukan lagi pasir untuk campuran semen sekitar dua truk di luar plasteran, sementara untuk pengecoran dibutuhkan semen sekitar tiga puluh sak.
Bahan material seperti besi, semen, dan seng didatangkan dari Galesong dengan menggunakan perahu jolloro. Bahan material lain diambil di pulau sendiri seperti pasir dan batu karang untuk pondasi. Menurut Daeng Tarang, awal-awal warga membangun rumah batu, mereka mengambil masing-masing batu di laut. Perlahan, telah ada beberapa warga yang berprofesi sebagai pengumpul batu. Mereka mengumpulkan lalu menjualnya kepada warga lain. Prosesnya, ketika aktivitas memancing dan menyelam telah selesai di laut, barulah mereka kemudian singgah mengambil batu karang sebelum perjalanan pulang ke rumah.
Untuk pembangunan rumah batu ini, sewa tukang yang harus dibayar oleh tuan rumah sekitar 8 juta rupiah. Menurut Daeng Tarang, ia dibayar dengan jumlah itu ketika rumah sudah selesai dikerjakannya. Kadang ia mengembalikan 2 juta rupiah kepada pemilik rumah, utamanya jika pemilik rumah masih kerabatnya sendiri. Sebagai tukang batu di kampungnya, Daeng Tarang tidak pernah mengambil gajinya setiap minggu. Ia hanya mengambil gaji ketika rumah yang dikerjakannya sudah selesai. Meskipun pemilik rumah memberikannya, ia tetap akan menolaknya, karena menganggap uang itu akan cepat habis ketika diambil per minggunya.
Persoalan Sosial-Lingkungan
Maraknya pembangunan rumah batu di Pulau Satangnga menyebabkan beberapa perubahan sosial-ekologis. Salah seorang warga Dusun Satangnga Raya, Daeng Tika, menyebut bahwa sejak tahun 1980-an hingga sekarang diperkirakan Pulau Satangnga telah berkurang sekitar lima puluh meter daratannya. Menurutnya ini terjadi karena material bangunan di Satangnga diambil dari laut.

Selain itu, terdapat penambangan pasir yang beroperasi di Satangnga selama tiga bulan pada tahun 2017, namun kala itu berhasil diusir oleh warga. Selain dua hal tersebut, susutnya pulau tersebut juga diakibatkan oleh proyek pembangunan jalan setapak dari pemerintah desa. Hampir seluruh jalan di Satangnga dibuat dengan menggunakan batu bata yang materialnya adalah pasir yang diambil dari bibir pantai. Beberapa lubang besar masih bisa dijumpai di bibir pantai Pulau Satangnga. Beberapa dijadikan sebagai tempat sampah oleh warga dan sebagian lubang telah tertutupi oleh sampah. Melihat pemerintah desa mengambil pasir di bibir pantai untuk proyek pembangunan, masyarakat yang tidak memiliki lahan juga kemudian turut mengambil pasir.
Akibat dari pengambilan pasir ini, perubahan kondisi laut di Satangnga terjadi. Salah seorang penyelam di Satangnga Raya mengatakan kalau saat ini ia harus tahan berjam-jam di laut atau di atas perahu. Di pesisir pantai ikan sudah semakin sedikit. Meskipun harus melaut lebih jauh, ia dan temannya tetap melakukannya. Situasinya menjadi lebih mendesak ketika sudah memiliki istri dan anak yang harus dinafkahi. Keselamatan dalam menyelam biasanya menjadi nomor dua, yang utama adalah biaya hidup yang harus ditanggungnya sebagai kepala keluarga.

Selain biaya hidup, beberapa teman menyelamnya terdesak oleh angsuran kredit bank yang harus mereka bayar setiap bulan. Meski cuaca tidak baik mereka terpaksa tetap pergi menyelam. Bahkan telah ada yang mengalami kelumpuhan karena aktivitas menyelam. Tidak banyak pilihan lain, mereka harus menyelam dengan bantuan kompresor meskipun itu membahayakan jiwanya.
Perubahan kondisi laut bukan hanya diakibatkan oleh pengambilan pasir, melainkan juga oleh aktivitas pengeboman ikan. Dalam kunjungan terakhir, kami menyaksikan sekelompok orang dengan menggunakan perahu-perahu besar dalam jumlah yang cukup banyak yang diduga kuat akan melakukan pengeboman. Sebelum membuang bom ikan, biasanya kelompok pengebom ini akan melakukan patroli lebih dahulu untuk memeriksa apakah ada orang luar atau dari kedinasan terkait.
Beberapa kapal kecil berupaya untuk mendekati perahu kami. Menurut seorang informan, kehadiran kami waktu itu yang tengah mengobservasi area penggalian pasir yang merusak hutan bakau membuat kegiatan pengeboman itu tak jadi dilakukan. Kelompok pengebom ini disebut-sebut dapat menghasilkan uang dalam jumlah yang cukup besar dalam sekali aktivitas pengeboman: antara 50-100 juta rupiah. Kelompok ini, menurut informan kami, dianggap memiliki kekerabatan dengan beberapa oknum perangkat desa dan memiliki jaringan dengan pihak keamanan.
Penggunaan kompresor untuk menyelam dan bom untuk mencari ikan membuat kegiatan melaut saat ini kian berbahaya dan lebih banyak dilakukan oleh laki-laki. Para perempuan di Satangnga sudah tidak melaut lagi seperti yang pernah dilakukan Daeng Sugi. Para perempuan hanya fokus bekerja sebagai ibu rumah tangga. Pembagian kerja berbasis gender di setiap keluarga Satangnga kian tegas. Laki-laki bertugas mencari uang sementara perempuan mengurusi rumah tangga.
Warga Satangnga kini tampak berusaha memenuhi kebutuhan dengan beragam cara karena desakan hidup yang membutuhkan biaya besar. Mimpi kesejahteraan dan sarana pemenuhan kebutuhan masyarakat di Satangnga semakin terhubung oleh sistem sosial-ekonomi yang diperantarai oleh uang. Termasuk dalam hal pembangunan rumah. Namun, bayangan tentang kesejahteraan tersebut memiliki akibat pada kondisi sosial dan lingkungan yang diam-diam semakin menekan kehidupan masyarakat.
***
Catatan Akhir: ¹ Ini juga terkonfirmasi saat mengobrol Dengan Daeng Ngagi Kamase (80 Tahun) di Pulau Satangnga pada 2023 lalu. ² Riset Surya Saluang di Kepulauan Tanakeke pada tahun 2020 yang belum dirilis. ³ Leonard Y. Andaya, Warisan Arung Palakka: Sejarah Sulawesi Selatan Abad ke-17, Halaman 91-92, Penerbit Inninawa, Makassar, 2004. Dalam kisahnya, Speelman mengirim surat kapada karaeng Gowa di Makassar, yang bersisi tuntutan dan pertanggung jawaban Gowa terhadap terbunuhnya orang Belanda di Pulau Don Duongo (sekarang Pulau Dayang-Dayangang yang berada di sebelah utara Pulau Satangnga), dan 1.435 Coprijksdaalders yang diambil oleh nelayan Makassar di bangkai kapal Leeuwin, Speelman berkata ketika dikunjungi di Tanakeke oleh dua bangswan Gowa yang datang membawa emas sebanyak 1.056 emas untuk negosiasi atas kejadian tersebut. Tetapi negosiasi tersebut tidak memiliki titik temu dan Speelman berkata bahwa darah orang Belanda hanya dapat dibayar dengan dengan darah, bukan uang. Kemudian di Tanakeke yang merupakan kepulauan besar dari Satangnga, juga dijadikan sebagai tempat persinggahan dalam ekspedisi kompeni yang dipimpin oleh Laksmana Cornelis Janszoon Speelman pada tanggal 17 Desember 1666, dan menuju pantai Makassar dua hari kemudian. Tepat tanggal 21 Desember 1666, balasan Sultan Hasanuddin atas peristiwa tersebut, pihak kerajaan Gowa tidak merasa bersalah, dan membuat Speelman geram atas sikap Sultan Hasanuddin, hingga terjadi perang Makassar pertama di sekitar perairan Tanakeke, sebab Speelman dan sekutunya merasa pihak kerajaan Gowa tidak merasa menyesal, dengan itu Speelman memerintahkan seluruh armada Belanda untuk maju sekitar satu kilo meter dari pelabuhan Makassar, dan Tertholen sudah mulai membombardir Kota Makassar sebagai ancaman kepada pemerintah kerajaan Gowa. Dalam Instruksi Speelman menyebut ekspedisi kali ini, merupakan perang habis-habisan melawan Gowa, dengannya Speelman mengevaluasi laporan dari berbagai benteng dan beberapa bangsawan terkejut melihat armada Belanda tiba di perarain Tanakeke dengan jumlah yang sangat banyak. Perang Makassar secara mendadak dilakukan, dengannya persiapan-persiapan Gowa, untuk melawan kolonialisme dan sekutunya tidak terlalu matang. ⁴ Jejak peperangan ini juga dikonfirmasi dengan ditemukannya bahan peledak seperti bom oleh beberapa nelayan penyelam di Tanakeke. ⁵ Hasil Wawancara dengan Risal (25 tahun), ketua BPD Desa Mattiro Baji, di Rumah Daeng Tika, Dusun Satangnga Raya, 07 Februari 2023.